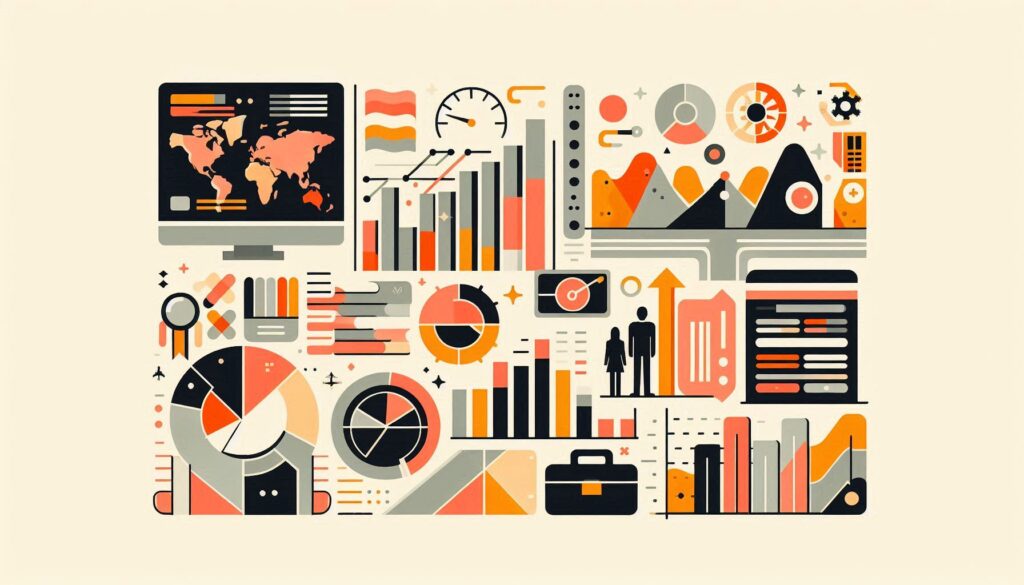Dalam momentum peringatan Hari Buruh (May Day), penting bagi kita untuk bersama sama melihat lebih dekat situasi terkini yang dihadapi oleh pekerja perempuan di Indonesia. Di tengah tekanan ekonomi dan ketidakpastian pekerjaan, terdapat pergeseran dimana semakin banyak perempuan mengambil peran sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Alasan yang mendasari adalah tekanan ekonomi dimana laki-laki (yang menempati posisi kepala keluarga) tidak mampu mendapatkan penghasilan tetap.
Data dari CNBC Indonesia menunjukkan bahwa setiap 1 dari 10 pekerja perempuan adalah tulang punggung keluarga, dan sebagian besar dari mereka berusia diatas 60 tahun (17,91%). Hal ini mengindikasikan lemahnya sistem perlindungan sosial bagi lansia. Kemudian, 55,84% dari perempuan pencari nafkah hanya menamatkan pendidikan sekolah dasar. Kondisi ini semakin membatasi kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.
Yang menarik lagi adalah posisi perempuan pencari nafkah ini dalam struktur keluarga, yaitu sebanyak 40,77%, berstatus sebagai istri. Dalam model keluarga patriarki, peran istri secara administratif adalah sebagai pendamping dari kepala keluarga. Ironisnya, kini bekerja/mencari nafkah malah dibebankan kepada mereka.
Secara umum, kerja atau labor (dalam bahasa inggris) dapat dipahami sebagai segala bentuk upaya produktif yang menghasilkan hasil luaran/output, baik berupa kerja berbayar, kerja tidak berbayar, pekerjaan rumah tangga, ataupun pekerjaan emosional. Salah satu kategori kerja yang sering luput dari perhatian adalah emotional labor atau kerja emosional. Konsep ini pertama kali disampaikan oleh sosiolog Arlie Hochschild dalam bukunya yang berjudul The Managed Heart (1983). Pekerjaan emosional ini mengacu pada pekerjaan yang mengharuskan individu untuk mengelola perasaan orang lain dengan mengorbankan perasaannya sendiri.
Hingga kini, konsep ini digunakan untuk menggambarkan pekerjaan yang kurang dihargai secara material, namun banyak dijalani oleh perempuan. Contohnya, pekerjaan di bagian pelayanan publik, pengelolaan rumah tangga, kegiatan sosial di kantor, ataupun hubungan personal, yang sering kali tidak mendapat rekognisi dari segi biaya waktu, tenaga, dan stress yang telah dicurahkan.
Perempuan, selain berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, juga tetap bertanggung jawab atas pekerjaan emosional yang masih dianggap sebagai “tugas alami” perempuan dalam konstruksi patriarki. Misalnya, pekerjaan pengasuhan dan tanggung jawab rumah tangga. Dalam perspektif feminis, beban ganda ini dikenal sebagai second shift, istilah yang juga dicetuskan oleh Arlie Hochschild melalui bukunya The Second Shift (1989). Beban ganda ini tentu aja memiliki berbagai implikasi terhadap perempuan. Misalnya, perempuan memiliki risiko mengalami stress dan kelelahan yang lebih tinggi daripada laki-laki karena harus menyeimbangkan antara pekerjaan yang dibayar dan pekerjaan yang tidak dibayar.
Di Indonesia, perempuan merupakan bagian signifikan dari tenaga kerja yang tersebar di sektor formal dan informal. Namun, perlindungan hukum dan pengakuan terhadap kontribusi mereka masih minim. Meskipun ILO (Organisasi Perburuhan Internasional) pada tahun 2014 telah melaporkan penurunan ketimpangan gender di pasar tenaga kerja, diskriminasi di ranah domestik, hukum, dan juga upah masih terjadi. Salah satu contoh nyata adalah UU Cipta Kerja yang banyak dikritik karena lemahnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja perempuan, seperti pemberian upah yang setara, hak bersalin, dan lingkungan kerja yang aman.
Lemahnya perlindungan hukum ini semakin memperburuk kerentanan ekonomi yang dihadapi perempuan, terutama mereka yang bekerja di sektor informal di lingkungan kerja rumahan da pekerja outsourcing. Mengutip mahardhika.org, 80% tenaga kerja di industri garmen adalah perempuan, dan banyak diantaranya yang menyatakan bahwa pabrik bukanlah lingkungan yang aman bagi pekerja perempuan yang hamil dan menyusui. Masalah lain yang tak kalah mendesak adalah kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja. KOMNAS Perempuan melaporkan bahwa pekerja rumah tangga memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap kekerasan seksual, pelecehan seksual, hingga perdagangan manusia, terutama bagi pekerja migran.
Dinamika pekerja perempuan di Indonesia merupakan hal yang kompleks dan harus dilihat dari berbagai faktor, seperti sosial, ekonomi, hukum, dan juga budaya. Memahami masalah ini memerlukan eksplorasi mendalam tentang bagaimana pekerjaan perempuan yang secara sistematis acapkali dipinggirkan, dan implikasinya dalam melanggengkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, dalam memperingati Hari Buruh ini, penting untuk tidak hanya merayakan kontribusi para pekerja tetapi juga untuk secara kritis merenungkan ketidakadilan yang terus-menerus terjadi, terutama pada pengalaman perempuan dalam dunia kerja.
Sudah saatnya kebijakan harus dibuat agar mengakui dan menghargai semua bentuk pekerjaan, melindungi hak pekerja secara inklusif dan mendekonstruksi norma-norma patriarki yang mengeksploitasi perempuan melalui pembagian peran yang tidak setara. Hanya dengan demikian kita dapat bergerak menuju sistem masyarakat yang benar-benar adil dan setara untuk semua.